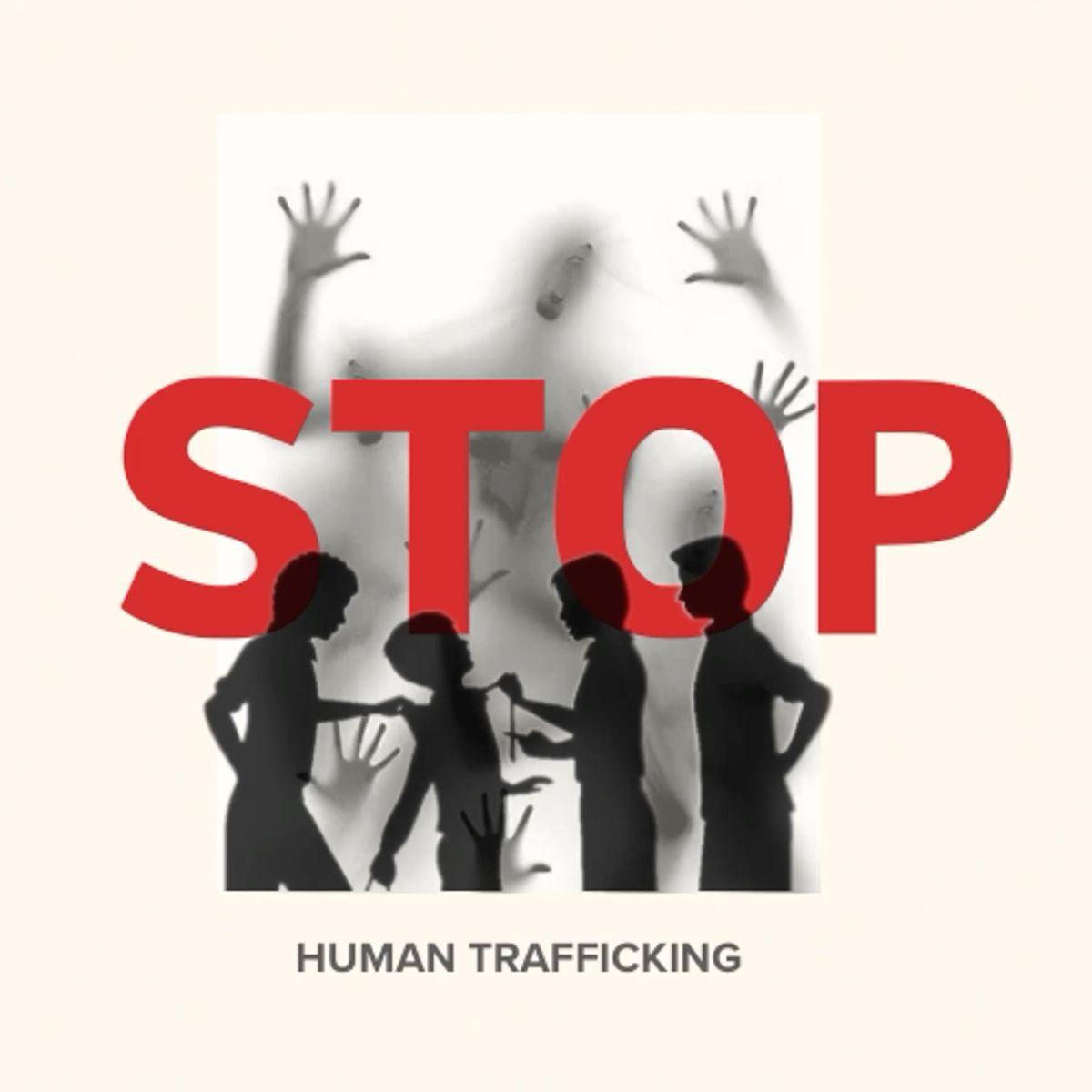Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional (hal. 3-4), Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku setiap subjek hukum, termasuk hubungan antara suatu negara dengan warga negaranya, antara negara-negara (termasuk organisasi internasional), antara satu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, antara organisasi internasional dengan individu-individu, atau antara individu dengan individu lainnya. Dalam Hukum Internasional juga mengatur bagaimana Hak Asasi Manusia yang harus dihormati setiap negara maupun individu.

Hak Asasi Manusia internasional sendiri dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang lebih dikenal di Indonesia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada pasal 1 DUHAM, mengakui bahwa semua orang mempunyai martabat yang sama. Hal ini memastikan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada, baik di negara mereka sendiri atau di negara lain, memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat berdasarkan martabat dan hak-hak dasar mereka. Setiap negara yang ikut andil dalam deklarasi ini, akan meratifikasi perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional. Negara berkomitmen untuk menerapkan peraturan-peraturan dan undang-undang domestik yang sesuai dengan kewajiban perjanjian mereka. Dengan menjadi pihak dalam perjanjian internasional, suatu negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan Hukum Internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. ‘Kewajiban untuk menghormati’ mengharuskan negara untuk tidak melakukan campur tangan atau pembatasan yang dapat menghalangi pemenuhan Hak Asasi Manusia. ‘Kewajiban untuk melindungi’ menuntut negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sementara itu, ‘kewajiban untuk memenuhi’ berarti negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang mendasar.
Di Indonesia, Hukum Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Aturan ini mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk memiliki, dan hak untuk menyampaikan pendapat, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, serta masyarakat. Penegasan ini juga terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan HAM, termasuk hak untuk hidup sejak dalam kandungan.
Dalam sebuah kasus yang terjadi pada bulan Juli 2024, sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI), terutama dari Bangka Belitung, menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Mereka dijanjikan posisi di sektor perhotelan di Mae Sot, Thailand, dengan gaji sebesar 26.000 baht per bulan (sekitar Rp12 juta). Para perekrut membentuk grup Telegram dan membagikan lokasi hotel yang tampak meyakinkan. Pada akhir Juli 2024, para korban memulai perjalanan dari Bangka ke Batam, kemudian menyeberang ke Johor, Malaysia, dan melanjutkan perjalanan darat ke Kuala Lumpur. Dari sana, mereka terbang ke Bangkok, Thailand, dan diangkut ke Mae Sot menggunakan kendaraan.
Setibanya di Mae Sot, para korban tidak ditempatkan di hotel seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka dibawa ke Myawaddy, Myanmar, dan disekap di kompleks yang dikelola oleh sindikat asal Vietnam. Di sana, mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring, menggunakan aplikasi kencan untuk mencari korban dan menyerahkan data calon korban kepada sindikat. Mereka menghadapi ancaman kekerasan fisik dan hukuman jika tidak memenuhi target harian. Kondisi hidup mereka sangat buruk, dengan makanan yang tidak sesuai dan akomodasi yang sempit. Wilayah Myawaddy juga merupakan daerah konflik antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak, menambah risiko bagi para korban. Penyekapan dan eksploitasi ini berlangsung dari Agustus 2024 – Februari 2025.
Pada awal tahun 2025, beberapa korban berhasil menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon melalui sesama WNI. Mereka harus berhati-hati karena paspor mereka ditahan dan gerak-gerik mereka diawasi. Pada akhir Februari 2025, aktivitas sindikat mulai terganggu akibat seringnya pemadaman listrik, memberikan kesempatan bagi para korban untuk melarikan diri. Pada 23 Februari 2025, mereka dievakuasi ke tangsi militer Myanmar, kemudian dipindahkan ke hotel, dan akhirnya dibawa ke Mae Sot, Thailand. Dari sana, mereka diterbangkan ke Jakarta pada 18 Maret 2025.
Setibanya di Indonesia, para korban langsung dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi dari pemerintah. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI di Yangon dan Bangkok, serta otoritas Myanmar dan Thailand, untuk memfasilitasi evakuasi dan pemulangan para korban. Pada Maret 2025, pemerintah juga melakukan penyelidikan terhadap agen perekrutan ilegal di Indonesia dan menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari tindak pidana perdagangan orang.
Dari kasus di atas dapat diketahui jika perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling keji dan merendahkan martabat manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dunia tertuju pada kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Myanmar. Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak dasar korban atas kebebasan, tetapi juga mengabaikan hak atas perlindungan, keamanan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, TKI yang diperjualbelikan atau dieksploitasi di Myanmar menjadi korban dari suatu kejahatan transnasional yang sistematis dan terorganisir.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000 (UNTOC) yang dilengkapi dengan Protokol Palermo tentang Pencegahan, Penindakan dan Penghukuman terhadap Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, secara gamblang menyatakan bahwa perdagangan orang mencakup “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya…” (Pasal 3(a) Protokol Palermo). Eksploitasi yang dimaksud mencakup kerja paksa dan perbudakan modern.
Dalam banyak kasus, TKI yang direkrut secara ilegal dan kemudian dikirim ke Myanmar dijanjikan pekerjaan layak. Namun, pada kenyataannya mereka dipaksa bekerja tanpa upah, mengalami kekerasan fisik maupun seksual, dan ditahan tanpa kejelasan hukum. Mereka dipaksa bekerja melebihi batas waktu kerja normal, diberikan fasilitas tempat tinggal yang kumuh. Dalam satu kamar, akan ditempati oleh belasan orang pekerja. Mereka juga diberi makan seadanya, atau bahkan sama sekali tidak makan. Akibat dari hal tersebut, banyak pekerja yang terjangkit penyakit. Namun, pihak perusahan sendiri tidak akan peduli terhadap hal tersebut dan akan kembali menyiksa mereka jika sampai mereka tidak bekerja.
Komplek perusahaan dan asmara pekerja akan dijaga ketat oleh penjaga bersenjata yang selalu aktif memantau aktivitas mereka dan menjaga keamanan lingkungan sekitar. Selain itu, dokumen pribadi, seperti paspor juga disita oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini, membuat para pekerja akan sulit sekali untuk keluar dari tempat yang mereka anggap sebagai neraka. Jika para pekerja ingin pulang ke negara asalnya, perusahaan akan meminta tebusan kepada pekerja tersebut dan pihak keluarga berupa uang dengan nominal yang besar atau orang pengganti untuk menggantikan mereka bekerja di perusahaan tersebut. Selain yang disebutkan di atas, beberapa para pekerja juga mengalami ancaman pengambilan organ tubuh. Semua praktik ini jelas melanggar Universal Declaration of Human Rights (UDHR), khususnya Pasal 4 yang melarang perbudakan dan Pasal 5 yang melarang penyiksaan. Indonesia sebagai negara asal dan Myanmar sebagai negara tujuan memiliki kewajiban untuk melindungi korban perdagangan manusia sesuai dengan prinsip state responsibility di bawah Hukum Internasional.
Meskipun Hukum Internasional telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, kenyataannya perlindungan bagi korban dan penuntutan terhadap pelaku seringkali menghadapi hambatan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum lintas negara (jurisdictional enforcement). Myanmar, pada kenyataannya, bukan merupakan pihak dalam Protokol Palermo, sehingga komitmennya untuk menerapkan standar internasional menjadi terbatas. Selain itu, situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di Myanmar, terutama setelah kudeta militer pada tahun 2021, semakin memperburuk penanganan kasus perdagangan manusia, karena fokus negara lebih diarahkan pada stabilitas politik dan militer.
Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa tidak ada perjanjian resmi terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Negara Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran yang berada di tiga negara tersebut berstatus ilegal. Sehingga sangat beresiko terjadinya pelanggaran HAM terhadap mereka dan akan sulit mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Karena tidak ada prosedur yang terstruktur dan aman, membuat perlindungan terhadap mereka menjadi terbatas, bahkan tidak ada.
Selain itu, koordinasi antar negara di kawasan Asia Tenggara masih belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat kerangka kerja regional seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), pelaksanaannya masih lemah dan tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang kuat, seperti yang ada di bawah PBB atau Mahkamah Internasional. Kurangnya komitmen hukum ini mengakibatkan lemahnya kerja sama internasional antara Indonesia dan Myanmar dalam upaya menyelamatkan korban TKI.
Peran agen perekrutan ilegal semakin memperumit situasi. Banyak TKI diberangkatkan tanpa mengikuti prosedur yang sah, sehingga tidak terdaftar oleh otoritas negara. Hal ini menyulitkan proses pelacakan dan repatriasi korban. Dalam banyak kasus, TKI yang menjadi korban tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, tidak mendapatkan perlindungan dari sistem hukum di negara tujuan, dan sering kali malah dikriminalisasi karena masuk secara ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip anti pengusiran atau larangan pengembalian (non-refoulement), yang melarang pengembalian korban ke negara asal bila mereka terancam bahaya, sering diabaikan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan negara, organisasi internasional, serta masyarakat sipil. Negara Indonesia harus memperkuat upaya pencegahan, termasuk pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja serta memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat yang rentan, yaitu melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tersebar melalui sosial media atau pihak tidak resmi (agen yang tidak terverifikasi dan memiliki izin resmi dari pemerinta). Pemerintah Indonesia juga turut memantau serta mengingatkan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memastikan setiap proses penempatan pekerja ke luar negeri dilakukan melalui proses yang resmi. Upaya ini dapat dilakukan melalui implementasi ketat terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Di tingkat internasional, Indonesia harus memperkuat kerja sama bilateral dengan Myanmar serta negara transit lainnya seperti Thailand atau Laos. Tujuannya adalah membentuk task force regional yang fokus pada penanganan perdagangan manusia, termasuk pemulangan dan rehabilitasi korban. Sementara itu, organisasi seperti International Organization for Migration (IOM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam proses investigasi dan pendampingan korban.
Lebih lanjut, diperlukan dorongan kuat agar ASEAN memperkuat mekanisme peninjauan pelaksanaan ACTIP dan membentuk pengadilan regional atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran HAM lintas batas.
Dalam jangka panjang, pendekatan Hak Asasi Manusia yang berfokus pada korban (victim-centered human rights approach) harus diintegrasikan dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi HAM Indonesia. Korban perdagangan manusia bukan hanya sekedar angka statistik, melainkan individu yang memiliki hak-hak yang perlu dipulihkan secara menyeluruh, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis.
Kasus perdagangan manusia yang menimpa TKI di Myanmar mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun Hukum Internasional telah menyediakan kerangka hukum yang kuat. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya komitmen negara, konflik politik, dan keterbatasan dalam penegakan hukum.
Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan kolaborasi lintas batas, reformasi hukum di tingkat nasional, serta penguatan diplomasi internasional yang berpihak pada korban. Hanya dengan pendekatan multilapis dan berorientasi pada korban, kita dapat mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi para TKI yang menjadi sasaran kejahatan kemanusiaan ini.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-internasional-lt628cc2a1ce846/
Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 8-9
https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law
https://satupersen.net/blog/pemerintah-larang-wni-kerja-di-myanmar-kamboja-ternyata-ini-penyebabnya
https://www.kompas.id/artikel/jalan-panjang-wni-korban-perdagangan-manusia-di-myanmar